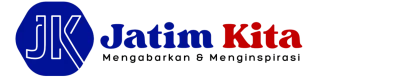“Jika kebijakan budaya hanya lahir dari satu atau dua figur yang merasa paling sah menafsirkan sejarah Sumenep, itu sangat berbahaya. Budaya dan sejarah adalah milik kolektif, bukan hak eksklusif individu atau kelompok tertentu,” tegasnya.
Menurutnya, Sumenep memiliki sejarah panjang dengan lapisan peradaban yang kompleks dari kerajaan, kolonialisme, hingga dinamika masyarakat pesisir dan agraris. Menetapkan satu model busana sebagai simbol resmi tanpa dialog publik berpotensi mereduksi kekayaan sejarah tersebut menjadi simbol tunggal yang dikendalikan oleh kekuasaan.
Lebih jauh, Syaf Anton mengingatkan potensi lahirnya hegemoni simbolik, yakni ketika simbol budaya digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan.
“Ketika ASN diwajibkan mengenakan simbol tertentu tanpa ruang bertanya dan berdiskursus, mereka berisiko hanya menjadi etalase visual kekuasaan. Padahal ASN seharusnya menjadi pelayan publik yang kritis dan berdaya,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pelestarian budaya sejatinya bertumpu pada kesadaran dan partisipasi, bukan kepatuhan administratif. Budaya yang hidup tumbuh dari pemahaman dan kebanggaan, bukan dari kewajiban formal.
“Busana bisa saja diwajibkan, tetapi martabat sejarah dan kebudayaan tidak bisa dipaksa tunduk pada peraturan. Ketika simbol budaya direduksi menjadi alat legitimasi politik, sejarah akan mencatatnya sebagai pengerdilan kebudayaan itu sendiri,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Sumenep belum memberikan keterangan resmi terkait proses perumusan Perbup Nomor 67 Tahun 2025, termasuk sejauh mana pelibatan budayawan, akademisi, dan pengrajin lokal dalam penetapan busana yang dimaksud.
Halaman : 1 2